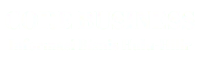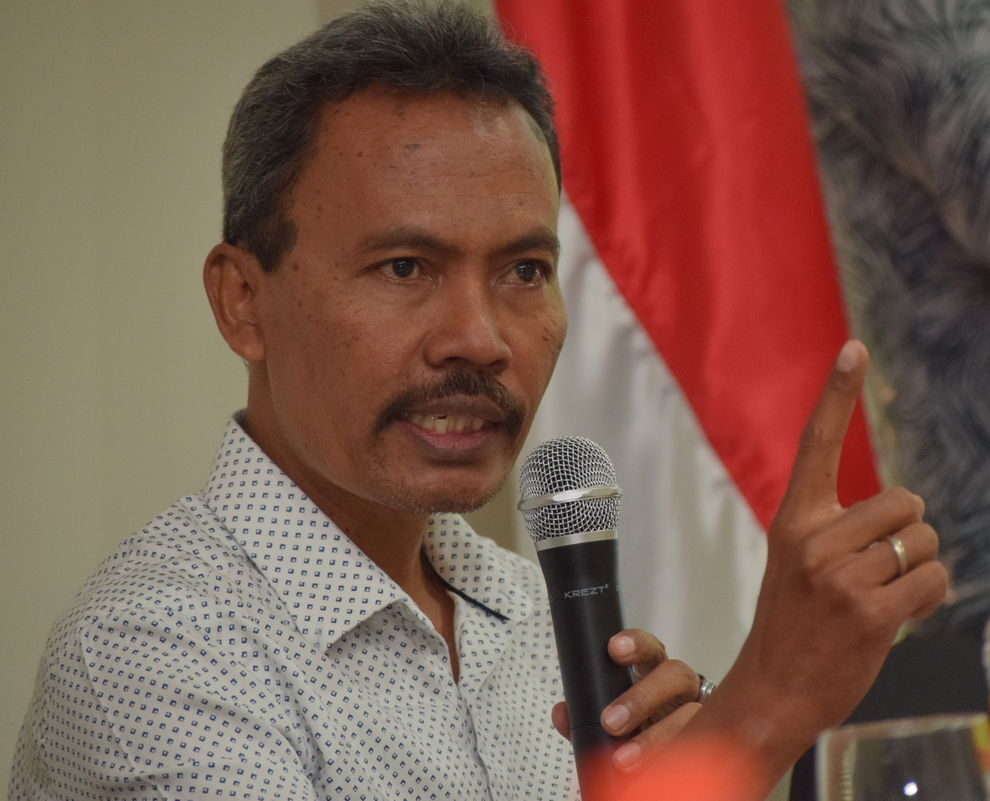Catatan Setahun Prabowo-Gibran di Bidang Pangan

Oleh: Khudori
SEJAK dilantik pada 20 Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto menargetkan swasembada pangan. Berulangkali ia menyampaikan bangsa yang besar akan terguncang apabila tidak mampu memenuhi pangannya. Politik bisa terganggu. Seperti tercantum di Asta Cita Kedua, Prabowo hendak mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, dan air. Asta Cita ini masuk prioritas nasional di RPJMN 2005-2029.
Dalam perjalanannya, swasembada pangan yang semula ditargetkan pada 2029 kemudian diubah untuk bisa dicapai secepat-cepatnya. Sampai setahun usia pemerintahan Prabowo, setidaknya bisa dibaca pencapaian swasembada pangan itu hendak menyontek dan memodifikasi apa yang dilakukan Presiden Soeharto selama Orde Baru. Salah satu prestasi Orde Baru mengubah dari importir beras jadi swasembada beras pada 1984.
Untuk mencapai swasembada beras, di pusat Soeharto membentuk Sekretariat Bimas. Pengorganisasian Bimas tersentral dipimpin langsung oleh Presiden. Untuk mendukung produksi padi dibangun pabrik pupuk dan benih BUMN, membenahi Bulog, membangun litbang pertanian, dan menggalakkan penyuluhan.
Untuk memastikan program bisa dieksekusi di tingkat bawah, di desa dibangun Catur Sarana Desa. Ini mencakup kios sarana produksi, BRI unit desa, penyuluhan unit desa (PPL), dan Badan Usaha Unit Desa/KUD. Kios sarana produksi bertugas menyediakan input produksi, BRI unit desa memastikan akses pendanaan, PPL menggaransi adopsi inovasi, dan BUUD/KUD membeli hasil produksi petani untuk disetor ke Bulog.
Memanfaatkan teknologi Revolusi Hijau yang berkembang saat itu, swasembada beras tercapai pada 1984. Produktivitas padi naik dari 1,8 ton gabah/ha jadi 3,01 ton gabah/ha hanya 14 tahun (1970-1984). Lonjakan dalam waktu singkat ini mengalahkan Jepang dan Taiwan. Jumlah penduduk berlipat tapi ketersediaan beras naik 300%: dari 7-8 juta ton (tahun 1960-an) menjadi 30-31 juta ton (tahun 2000-an).
Secara gradual, Prabowo membenahi berbagai aspek usahatani, termasuk membentuk institusi mirip Catur Sarana Desa. Pertama, membentuk 80 ribu koperasi desa/kelurahan merah putih (KDMP). Bukan hanya diandaikan menyediakan input produksi dan menampung hasil-hasil produksi pertanian, KDMP sepertinya juga akan difungsikan sebagai penyedia pendanaan bagi masyarakat desa, wabilkhusus petani.
Kedua, menaikkan volume pupuk subsidi menjadi 9,5 juta ton dan penyalurannya dipermudah. Regulasi berjenjang yang berjumlah 125 dipangkas tinggal beberapa biji. Ini untuk memudahkan akses petani terhadap pupuk subsidi. Ketiga, pemerintah pusat bisa mengintervensi pembenahan irigasi rusak yang menjadi tanggung jawab daerah. Keempat, menarik penyuluh ke pusat agar lebih efektif. Penyuluh tetap di daerah masing-masing, sebagai pegawai pusat yang bertugas di daerah.
Tentu belum semua pembenahan itu bisa dilihat apa dampak dan hasilnya. Karena sebagian besar masih berproses. Satu hal yang patut dicatat, keberhasilan Orde Baru mencapai swasembada beras karena ada sentralisasi politik, momentum Revolusi Hijau, dan investasi publik di sektor pertanian yang naik. Seperti pembangunan irigasi, jalan desa dan pertanian, pabrik pupuk, industri benih, riset hingga penyuluhan.
Saat ini lingkungan strategis sudah jauh berubah. Sejak otonomi daerah pada 2001, pusat harus berbagai kewenangan dengan daerah. Meski ada gejala resentralisasi dalam beberapa tahun terakhir, tapi sulit membayangkan akan terjadi sentralisme seperti di era Orde Baru. Sampai saat ini juga belum ada lompatan inovasi dan terobosan teknologi. Yang mengenaskan, investasi publik di sektor pertanian terus menurun.
Catatan lain, sejak dilantik sampai saat ini Prabowo dan para pembantunya di Kabinet Merah Putih belum pernah menjelaskan apa yang dimaksud dengan swasembada pangan. Apakah swasembada pangan diterjemahkan dalam swasembada komoditas, seperti era Presiden Joko Widodo dan Susilo Bambang Yudhoyono. Jadi, ada sekian komoditas yang ditargetkan swasembada. Atau swasembada berbasis gizi: swasembada karbohidrat, swasembada protein, swasembada lemak. Sumber karbohidrat bisa dari pangan apa saja.