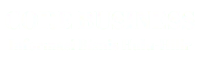PP Tarif Royalti sudah Diterbitkan, Menteri ESDM Tetap Hormati Masukan Pelaku Usaha

Sekretaris Umum Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), Meidy Katrin Lengkey menguraikan poin-poin keberatan pelaku usaha hulu dan hilir.
Meidy mengutarakan, perubahan tarif royalti ini berlaku kepada semua komoditi minerba, yang semakin menekan pelaku usaha, terutama di tengah berbagai tantangan ekonomi dan regulasi yang sudah ada.
Menurutnya, kenaikan royalti ini akan semakin membebani industri yang saat ini sudah menghadapi biaya operasional tinggi akibat berbagai faktor, seperti kenaikan harga biosolar (B40), penerapan UMR minimum 6,5 persen, serta kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen, Dana Hasil Ekspor (DHE) 100 persen, Global Minimum Tax 15 persen, kewajiban reklamasi pascatambang, iuran PNPB IPKH, hingga Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM).
“Kebijakan perubahan tarif royalti bahkan bisa mengganggu iklim investasi di Indonesia. Untuk komiditi nikel, misalnya, penerapan tarif bijih nikel antara 14-19 persen dan produk olahan nikel antara 5-7 persen, angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan Filipina, yang hanya menerapkan 5–7 persen untuk ore dan 2 persen untuk produk olahan,” kata Meidy di acara Diskusi dan Konferensi Pers ‘Wacana Kenaikan Tarif Royalti Pertambangan’ yang diselenggarakan APNI, di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (17/3/2025).
Bahkan, kata Meidy, tarif royalti baru jika dibandingkan dengan Australia masih lebih tinggi. Australia menerapkan royalti antara 5–7,5 persen untuk ore dan 2–5 persen untuk produk olahan. Kemudian Brasil yang menerapkan 2–5 persen untuk ore dan 1–3 persen untuk produk olahan.
Menurutnya, jika tarif royalti dinaikkan tanpa mempertimbangkan berbagai faktor, maka daya saing Indonesia dalam menarik investasi di sektor hilirisasi minerba bisa terancam.
Karena itu, APNI berharap pemerintah mempertimbangkan kembali kebijakan ini agar tidak menghambat pertumbuhan industri hilirisasi yang menjadi salah satu motor utama ekonomi Indonesia. (Rif)