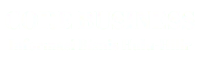Darurat! APNI Serukan Kontrol Produksi dan Standar ESG untuk Selamatkan Industri Nikel Nasional

Jakarta,corebusiness.co.id-Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) menyerukan pentingnya pengendalian produksi dan penerapan standar ESG nasional menyusul keprihatinan mendalam terhadap kondisi oversupply yang menekan harga dan merugikan pelaku industri hulu.
Laporan terbaru dari lembaga internasional mengungkap bahwa lebih dari 50 persen pasokan nikel dunia saat ini berasal dari Indonesia. Namun, permintaan global, terutama dari sektor baterai dan stainless steel, belum mampu menyerap lonjakan pasokan. Hal ini menyebabkan harga nikel global terus melemah, margin menyempit, dan tekanan terhadap pelaku IUP semakin berat.
“Kita tidak bisa hanya fokus menambah kapasitas tanpa memperhatikan permintaan. Ini saatnya pemerintah melakukan kontrol produksi dan menyesuaikan arah hilirisasi,” kata Sekretaris Jenderal APNI, Meidy Katrin Lengkey, melalui keterangan tertulis, Kamis (31/7/2025).
Data dari Ferroaloy menunjukkan bahwa produksi NPI Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun, sementara Feni tetap kecil porsinya. Ini menandakan dominasi strategi volume tanpa evaluasi daya serap pasar.
Selain pengendalian produksi, APNI juga mendorong penerapan standar ESG nasional sebagai bentuk komitmen terhadap praktik pertambangan berkelanjutan. Langkah ini juga penting untuk mempertahankan akses pasar ekspor, terutama ke negara-negara yang menuntut transparansi lingkungan dan sosial.
APNI berharap pemerintah dapat segera meninjau ulang kebijakan RKAB, HPM, serta arah hilirisasi agar industri nikel nasional tetap kompetitif dan berkelanjutan di tengah tantangan global.
Satu sisi Meidy menyampaikan apresiasi Indonesia telah menjadi produsen utama nikel dunia (>50 persen pangsa pasar global). Di sisi lain, ekspansi produksi yang agresif tanpa pengendalian telah menciptakan kelebihan pasokan (oversupply) yang menekan harga dan membahayakan kelangsungan usaha pertambangan dan pengolahan nikel.
Ia menyebutkan permasalahan utama terjadinya oversupply tersebut. Pertama, kelebihan kapasitas produksi smelter (HPAL & RKEF). Kedua, permintaan hilir belum mampu menyerap output. Ketiga, harga LME dan SMM turun signifikan.

Kemudian kelima, banyak smelter beroperasi pada kondisi rugi. Keenam, adanya tekanan ESG dari pasar global. Ketujuh, perubahan RKAB dari 3 tahun menjadi 1 tahun, kenaikan PPN, royalti, dan regulasi fiskal belum adaptif.
Meidy mengungkapkan dampak yang ditimbulkan dari permasalah-permasalah di atas, antara lain terjadi penurunan harga jual bijih nikel, bisa menimbulkan ketidaklayakan ekonomi hilir, muncul kesenjangan antara regulasi dan kenyataan pasar, dan eksistensi industri nasional bisa terancam.
Terkait kondisi memprihatikan ini, APNI menyampaikan rekomendasi. Pertama,
pemerintah harus moratorium ekspansi smelter baru hingga keseimbangan tercapai. Kedua, RKAB tetap 3 tahun. Ketiga, perumusan ulang HMA/HPM agar mencerminkan real cost dan market.
Berikutnya keempat, penyusunan peta jalan hilirisasi berbasis permintaan global. Kelima, pembentukan standar ESG nasional. Dan keenam, diversifikasi pasar ekspor dan skema insentif untuk proyek berkualitas tinggi.
Meidy menyatakan, tanpa intervensi kebijakan, Indonesia berisiko memasuki siklus boom-bust berkepanjangan.
“APNI mendorong kolaborasi bersama untuk menata ulang arah industri nikel nasional agar lebih sehat, kompetitif, dan berkelanjutan,” pungkasnya. (Rif)