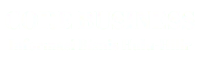Aspebindo Respons Rencana Kemenkeu Terapkan Bea Keluar Batubara dan Emas Tahun 2026

Jakarta,corebusiness.co.id-Ketua Umum Asosiasi Energi, Mineral, dan Batubara (Aspebindo), Anggawira meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) duduk bersama dengan pelaku hulu dan hilir sebelum memberlakukan tarif bea keluar (BK) terhadap komoditas batubara dan emas mulai tahun 2026. Pasalnya, penerapan BK yang mendadak, salah satunya berisiko mengganggu kontrak internasional dan reputasi pasokan Indonesia.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan memanfaatkan berbagai instrument fiskal yang relevan yang bisa memberikan kontribusi pemasukan negara. Salah satunya, pemerintah mewacanakan akan memungut tarif bea keluar (BK) terhadap komiditas batubara dan emas pada tahun 2026.
Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, penerapan BK sesuai dengan Pasal 2A UU No.17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Menurutnya, BK bertujuan antara lain untuk menjaga ketersediaan supply di dalam negeri dan atau menstabilkan harga komoditas.
Penerapan BK dengan memperhatikan pengembangan komoditas dari kementerian/lembaga pembina sektor. Selain itu, penerapan BK juga memperkuat ruang fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Saat ini BK diterapkan pada komoditas mineral maupun nonmineral. Namun, untuk komoditas batubara dan emas baru akan diberlakukan tahun 2026,” kata Purbaya saat rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Senin (8/12/2025).
Kemenkeu menargetkan penerimaan negara dari BK untuk komoditas batubara sebesar Rp 20 triliun dan emas Rp 3 triliun per tahun.
Terpisah, Ketum Aspebindo, Anggawira berpandangan, setidaknya ada lima faktor utama yang perlu diperhatikan Kemenkeu dalam menentukan besaran BK batubara dan emas. Pertama, ketentuan BK perlu disesuaikan dengan harga batubara dan emas di level internasional (benchmark-based). BK harus bersifat progresif mengikuti rentang harga (price-based sliding tariff), bukan tarif tetap.
Kedua, disesuaikan dengan struktur biaya produksi nasional. Termasuk biaya stripping batubara dan emas, logistik, royalti, pajak daerah, dan biaya keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan (K3L).
Ketiga, memperhatikan peran komoditas terhadap ketahanan energi dan hilirisasi batubara untuk Domestic Market Obligation (DMO), gasifikasi, dan energi transisi harus diperlakukan berbeda.
Keempat, kondisi pasar ekspor dan kontrak jangka panjang. Penerapan BK yang mendadak berisiko mengganggu kontrak internasional dan reputasi pasokan Indonesia.
Kelima, dampak terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) total, bukan hanya BK.
“Jangan sampai BK naik, tapi royalti, PPh, dan volume produksi justru turun,” kata Anggawira kepada corebusiness.co.id, Selasa (9/12/2025).
Selain itu, Anggawira menekankan poin krusial dalam desian penentuan tarif BK antara raw material dan intermediate product dari komoditas tersebut. Menurutnya, besaran tarif BK terhadap raw material seperti batubara thermal mentah dan bijih emas, wajar dikenakan lebih tinggi sebagai disinsentif ekspor bahan mentah, selama ada kesiapan infrastruktur hilir di dalam negeri.
“Sementara untuk intermediate product seperti coal upgrading, refined gold, dan logam turunan, seharusnya sangat rendah atau nol. Karena dalam proses produksi intermediate product, perusahaan telah menggelontorkan investasi, menciptakan lapangan kerja, dan berperan dalam memperpanjang rantai nilai domestik. Intinya, BK harus menjadi “penunjuk arah industrialisasi”, bukan sekadar alat pungutan,” jelasnya.
Insentif untuk Industri Hilir
Anggawira mengatakan bahwa Aspebindo mendukung wacana Menkeu Purbaya dalam hal pemberian insentif kepada investor atau perusahaan yang ingin membangun proyek transisi energi dari batubara. Seperti pembangunan industri pengolahan dimethyl ether (DME), gasifikasi, metanol, dan produk turunan batubara lainnya.
“Untuk menarik investor masuk ke proyek hilirisasi dan transisi energi dari batubara, insentifnya harus komprehensif dan bankable,” ujarnya.
Disebutkan, upaya-upaya untuk menarik investor antara lain:
- Fiscal incentives, seperti tax holiday jangka panjang (15–20 tahun), accelerated depreciation, PPN dan bea masuk ditanggung pemerintah untuk Engineering Procurement and Construction (EPC) dan peralatan.
- Price & offtake guarantee, melalui skema jaminan harga produk (DME substitution LPG) dan offtaker BUMN yang jelas dan jangka Panjang.
- Risk sharing government, dengan memberikan dukungan sovereign guarantee dan Viability Gap Fund (VGF) untuk proyek awal.
- Regulatory certainty, untuk kepastian tata kelola karbon, sinkronisasi ESDM–Kemenkeu–KLHK, dan perizinan satu pintu yang cepat dan pasti.
“Tanpa kombinasi insentif tersebut, proyek gasifikasi akan selalu ekonominya kalah oleh energi fosil impor,” kata Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) tersebut.
Selain itu, Anggawira juga mengungkapkan kendala utama perusahaan tambang batubara. Diutarakan, realistisnya ada lima kendala struktural yang masih dihadapi para pelaku hulu. Pertama, ekonomi proyek belum kompetitif. Harga produk hilir sering kalah dibanding LPG atau BBM impor.
Kedua, tingginya kebutuhan capex dan teknologi. Bahkan sebagian besar teknologi masih impor dan mahal.
Ketiga, kepastian pasar dan offtaker yang belum kuat. Karena itu, tanpa kontrak jangka panjang, proyek sulit dibiayai bank.
Keempat, belum optimalnya sinkronisasi kebijakan lintas kementerian terkait urusan fiskal, energi, industri, dan lingkungan.
Kelima, persepsi risiko regulasi jangka panjang. Investor masih khawatir perubahan kebijakan di tengah jalan.
Anggawira menyatakan, bagi Aspebindo, kunci kebijakan BK bukan pada besar atau kecil tarif, melainkan pada desain kebijakan yang konsisten, adil, dan pro industrialisasi.
Jika BK dirancang sebagai bagian dari industrial policy framework yang utuh—bukan pendekatan fiskal jangka pendek—maka BK batubara dan emas justru bisa menjadi instrumen transformasi ekonomi nasional, bukan hambatan investasi. (Syarif)