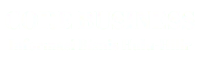IESR Wanti-wanti Pembangunan PLTN Pertama di Indonesia

Jakarta,corebusiness.co.id-Executive Director Institute for Essential Services Reform (IESR), Febby Tumiwa menyatakan, membangun infrastruktur energi harus dikaji secara teliti dari berbagai aspek. Salah satunya menyoal rencana pemerintah membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) pertama di Indonesia.
Payung hukum yang menangungi pembangunan PLTN pertama sudah dibuat pemerintah, baik dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional (RPP KEN) sebagai pengganti PP Nomor 79 Tahun 2014 tentang KEN, Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN), hingga Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034.
“Kalau kita baca dari beberapa pernyataan (di media massa), yang mau dibangun itu bukan PLTN konvensional, tapi Small Modular Reactor (SMR). Saat ini SMR baru beroperasi tiga unit, dua di Rusia dan satu unit lagi di China. Saya tidak tahu, Indonesia mau pilih reaktor nuklir konvensional atau SMR. Terlebih, kita belum ada penelitian soal SMR,” kata Febby menjawab pertanyaan corebusiness.co.id di acara Aspebindo Energy Executive Forum bertema “Peluang dan Tantangan Menuju Ketahanan dan Kemandirian Energi Nasional”, di Jakarta, Senin (17/11/2025).
Pemerintah menargetkan PLTN pertama sudah beroperasi antara tahun 2032 atau tahun 2034. Namun, untuk urusan pemilihan tipe reaktor PLTN saja, kata Febby, sudah muncul banyak pertanyaan. Misalnya, ketika pemerintah memutuskan memilih SMR, apa saja dasar pertimbangannya, kemudian soal pengoperasian dan maintenance, hingga pertimbangan keamanan.
“Kalau mau dibangun PLTN konvensional generasi 3+, misalnya jenis reaktor air ringan (Light Water Reactor/(LWR), apakah menggunakan tipe Pressuerized Water Reactor (PWR) atau Bolling Water Reactor (BWR)?” tanyanya.
Febby mengakui bahwa Indonesia mempunyai cadangan thorium dan uranium untuk bahan bakar reaktor nuklir. Namun, penggunaan thorium dan uranium untuk pembangkit listrik tidak sesederhana batubara. Setelah thorium atau uranium ditambang, lalu dimasukkan ke reaktor nuklir.
Berbeda dengan batubara, setelah diambil dari galian tambang bisa langsung dijadikan bahan bakar Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Namun, untuk bahan baku thorium dan uranium harus melalui proses peleburan (fusi) untuk menjadi bahan bakar untuk reaktor nuklir. Prosesnya lebih panjang.
Dikatakan Febby, industri peleburan thorium dan uranium untuk menjadi bahan bakar reaktor nuklir belum ada di Indonesia. Negara yang memproduksi thorium dan uranium bisa dihitung jari, seperti Rusia, China, Kanada, Amerika, dan Prancis.
“Bahkan, kalau kita punya cadangan thorium dan uranium, ekonomis tidak untuk ditambang. Karena PLTN berkaitan dengan teknologi. Biaya terbesar pembangunan PLTN bukan dari biaya bahan bakarnya, tapi dari sisi capital expenditures (Capex),” imbuhnya.
Febby menyampaikan, berdasarkan referensi data terbaru harga satu unit PLTN generasi 3+ untuk skala 1.200 megawatt (MW) dan 1400 MW antara US$ 8,5 miliar hingga US$ 10 miliar. Harganya lebih mahal dibandingkan SMR, karena ukurannya lebih kecil.
“Jika Indonesia ingin beli reaktor nuklir NuScale Power dari Amerika Serikat, yang katanya mau dibangun di Kalimantan Barat, harganya antara US$ 6,5 juta hingga US$ 7 juta per MW. Saya perkirakan harga listrik yang diproduksi dari reaktor nuklir tipe SMR ini 25 cent per kilowatt hour (kWh). Pertanyaannya, mau subsidi atau tidak untuk harga listrik tersebut. Karena capex-nya mahal,” tukasnya.
Ia menekankan, jangan sampai membangun infrastruktur energi nantinya menjadi beban publik terus menerus. Indonesia ingin ketersediaan energinya aman dan mandiri, namun terlebih dulu dikaji dari berbagai aspek pendukung, mulai dari perencanaan, pembangunan, pengoperasian, maintenance, keamanan, hingga harga listrik yang dijual ke rakyat.
Kalau ujung-ujungnya harga listriknya mahal, Febby khawatir, nanti rakyat yang mensubsidi melalui pajak. Semakin berat beban ekonomi negara, pemerintah mengeluarkan kebijakan menaikkan tarif pajak. (Rif)