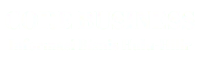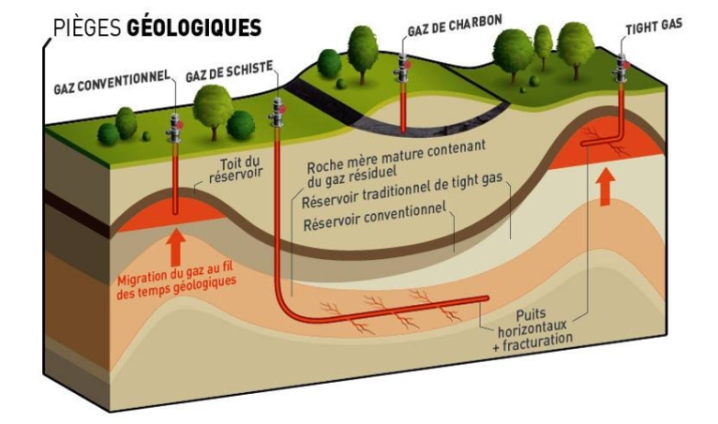Bob S. Effendi Urai Kontradiktif dan Solusi Rencana Pembangunan PLTN di Indonesia

Jakarta,corebusiness.co.id-Konsultan nuklir dan cyber security, Bob S. Effendi membedah rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) yang sudah diproyeksikan Pemerintah Indonesia. Selain mengungkap sisi kontradiktif, dia juga memberikan solusi.
Bob S. Effendi tengah berdiri di teras ketika corebusiness.co.id masuk ke pelataran halaman rumahnya yang cukup luas dan hijau di kawasan Pejaten Barat, Jakarta Selatan, Rabu pagi (26/3/2025), pukul 08.30 WIB.
“Jangan kaget ya, di dalam rumah saya banyak kucing,” bilang Bob S. Effendi saat mempersilakan corebusiness.co.id masuk ke ruang utama bangunan rumah permanen tersebut.
Kucing-kucing dari berbagai ras itu terlihat begitu jinak kepada majikannya. Beberapa di antaranya langsung mendekat, menghampiri Bob S. Effendi.
“Puluhan kucing saya ini sebagian berasal dari kucing liar yang tidak terawat. Di sini mereka kita rawat, setiap hari dikasih makan, dibersihkan, dan dijaga kesehatannya. Kebetulan istri saya, Kiki Rezki Effendi mempunyai tujuh klinik untuk hewan peliharaan di seluruh Indonesia, termasuk di Bali. Namanya Amore Animal Clinic,” cerita kakak sulung dari aktor dan politikus Dede Yusuf Macan Effendi.
Sejurus kemudian, mantan Direktur Operasi PT Thorcon Power Indonesia ini memulai perbincangan seputar industri nuklir. Bob menuturkan, selama sepuluh tahun bergabung di Thorcon, tenaga dan pikirannya terpusat rencana perusahaan ini ingin membangun PLTN di Pulau Kelasa, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung.
Lantaran itu, dirinya terus membangun relasi dan komunikasi dengan pihak pemerintah, termasuk kementerian dan lembaga terkait. Baik untuk urusan perizinan, feasibility study, hingga ketentuan lainnya yang harus dipenuhi Thorcon terkait rencana pembangunan PLTN tersebut.
“Sekarang pintu nuklir di Indonesia sudah terbuka, dan saya telah berhasil menempatkan Thorcon di posisi terdepan dan terpandang. Sekarang waktunya move on. Meskipun saya sudah tidak bergabung di Thorcon, tetap konsisten dalam sektor nuklir, tetapi sebagai konsultan nuklir bagi pemerintah dan beberapa perusahaan nuklir lainnya. Saya rasa setelah sepuluh tahun menggeluti nuklir, saya satu-satunya yang menguasai seluk-beluk sektor ini. Selain itu saya juga memulai jasa konsultan cyber security, termasuk pengembangan blockchain database,” ucap Bob, begitu sapaan akrab pria berkacamata tersebut.
Bob lantas memaparkan proyeksi pembangunan PLTN oleh Pemerintah Indonesia, dengan segala kontradiktif kebijakan yang dinilai masih mengganjal perusahaan-perusahaan nuklir.
Ia memulai dari Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Rencana pembangunan di undang-undang ini dibagi empat tahap. Tahap I Tahun 2025-2029 tentang Penguatan Transformasi, Tahap II Tahun 2030-2034 Akselerasi Transformasi, Tahap III 2035-2039 Ekspansi Global , dan Tahap IV Tahun 2040-2045 Perwujudan Indonesia Emas.
UU Nomor 59 Tahun 2024 mengamanatkan bahwa PLTN pertama di Indonesia beroperasi di Tahap II Tahun 2030-2034. Pada Tahap III Tahun 2035-2029 ekspansi PLTN. Bob menangkap kalimat itu bahwa pada Tahap III pembangunan PLTN sudah berkembang, baik dari sisi jumlah PLTN, kapasitas, ukuran, dan lainnya.
Yang menarik perhatian dirinya, pada Tahap IV Tahun 2040-2045, tertulis: terbangunnya industri nuklir. Lagi, Bob menyampaikan pemahaman dari kalimat itu, bahasanya adalah dengan kemandirian teknologi PLTN.
“Artinya, pada Tahap IV Indonesia harus sudah bisa membangun PLTN dengan desain sendiri termasuk industri nuklir dan rantai pasok nasional,” katanya.
Bob menilai rancangan dari Bappenas ini memiliki arah yang bagus sebagai grand strategy pengembangan industri nuklir di Indonesia, yang seharusnya sejak dulu sudah dibuat oleh Batan. Sementara saat ini grand strategy nuklir yang disebut Rencana Induk Ketenaganukliran masih dalam pembahasan direvisi UU Ketenaganukliran yang belum dimasukkan prolegnas. Karena itu, grand strategy yang sudah tertuang dalam UU Nomor 59 Tahun 2024 harus menjadi dasar nantinya bagi Rencana Induk Ketenaganukliran yang lebih detail dalam revisi UUK sebagai payung hukum dalam pengembangan potensi-potensi ketenaganukliran melalui tahapan identifikasi .
Sebagai gambaran, Bob melihat Korea Selatan dan Jepang yang baru membangun PLTN di awal tahun 1970-an. Kedua negara ini baru berhasil membangun industri nuklir setelah 30 tahun pembangunan PLTN pertama. Indonesia, mengacu UU Nomor 59 Tahun 2024, diproyeksikan tenggat waktu pembangunan industri nuklir sekitar 25 tahun, persisnya setelah pembangunan PLTN pertama. Lebih cepat 5 tahun dibandingkan Korea Selatan dan Jepang, seharunya bisa dan mampu karena sudah ada contohnya bahkan Indonesia dapat belajar dari Korsel dan Jepang.
Maka, saran Bob, desain PLTN pertama yang dibangun harus menjadi desain dasar menuju desain nasional PLTN merah putih nantinya termasuk pengembangan rantai pasok dan bahan bakar.
Mencontoh langkah yang ditempuh Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN) melalui PT Nurtanio, yang kemudian berganti nama menjadi PT Dirgantara Indonesia (PTDI), menggunakan desain lisensi perusahaan Spanyol, yaitu Construcctiones Aeronauticas SA (CASSA), ketika membuat pesawat penumpang sipil dan militer bermesin turboprop CN-212. Tahap berikutnya, IPTN kembali menggunakan desain lisensi CASSA untuk pembuatan pesawat NC-235.
“Jika kita perhatikan, ketika pembuatan pesawat CN-212, posisi huruf C ada di awal. Sementara pesawat NC-235, huruf N berada di depan. Karena, desain untuk pesawat NC-235 dibuat oleh Nurtanio, meskipun tetap menggandeng CASSA. Artinya, hak paten desain pesawat NC-235 milik Nurtanio dan CASSA,” urainya.
Dalam perjalannya, sebelum terjadi krisis moneter tahun 1998, Nurtanio membuat pesawat N-250 Gatot Kaca. Pesawat penumpang sipil (airliner) regional komuter turboprop ini 100 persen rancangan asli Nurtanio. Nurtanio juga sudah mendesain pesawat jenis jet N-2130.
Roadmap IPTN dalam membangun industri pesawat terbang, dari semula menggandeng CASSA hingga mendesain pesawat hasil karya anak bangsa sendiri, bisa dilakukan Pemerintah Indonesia dalam membangun industri nuklir. Ketika di antara tahun 2040 dan 2045 Indonesia mempunyai industri nuklir sendiri, bisa dilihat secara paralel bagaimana Nurtanio membangun industri pesawat terbang.
Pemerintah Indonesia, kata dia, bisa menggandeng perusahaan nuklir dari negara lain untuk desain pembangunan PLTN pertama. Kerja sama harus dijadikan satu paket dalam pengembangan desain dari pembangunan PLTN pertama hingga menjadi desain PLTN nasional. Desain PLTN tersebut harus cocok dengan pengembangan komponen ikutan yang dapat dibuat di Indonesia, termasuk pengembangan bahan bakar nuklir mengingat Indonesia sangat banyak uranium dan thorium. Hal ini berkaitan dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
“Jadi, pembangunan PLTN, industri nuklir, hingga pengembangan industri ikutan, harus dilihat secara komprehensif. Itu poin penting pertama,” tukasnya.
Poin penting kedua, Bob melihat masih ada undang-undang yang masih terkatung-katung pembahasannya di DPR, yaitu Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET). Salah satunya karena ada pro kontra terkait ketentuan power wheeling. RUU EBET juga mengatur tentang industri nuklir di Indonesia.
“Dalam RUU EBET, saya melihat sisi signifikan dalam hal pembiayaan PLTN. Dalam RUU EBET disebutkan ada mandat untuk pembiayaan EBET harus menjadi prioritas, baik melalui pembiayaan fiskal, hingga pemberian insentif,” katanya.
Di sisi lain, Bob menyoroti Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional (RPP KEN) sebagai pengganti PP Nomor 79 Tahun 2014 tentang KEN, yang sudah disetujui DPR dan pemerintah menjadi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam RPP KEN diamanatkan tahun 2032 PLTN pertama sudah beroperasi dengan kapasitas sekitar 11 persen atau sekitar 54 GW pada tahun 2060.
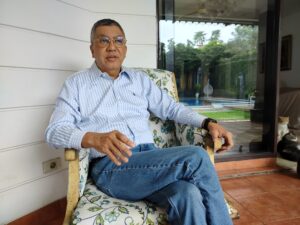
RPP KEN, sambungnya, juga mengamanatkan pembentukan Komite Pelaksana Program Energi Nuklir atau KP2EN (Nuclear Energy Program Implementing Organization/NEPIO). Dalam struktur organisasinya, KP2EN diketuai Presiden RI dengan Wakil Presiden sebagai wakil ketua. Menteri ESDM menjabat sebagai Ketua Harian NEPIO. Adapun posisi wakil ketua harian sekaligus ketua kelompok kerja (pokja) akan diisi orang dengan kompetensi yang tepat. Anggota NEPIO terdiri dari Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), menteri/kepala lembaga terkait, dan anggota DEN.
“KP2EN ini penting segera dilahirkan, karena saat ini tidak ada yang berani mengambil keputusan perihal PLTN semua menunggu lahirnya KP2EN. Bahkan menurut saya tidak perlu menunggu lahirnya RPP KEN dapat segera dibentuk melalui Perpres,” terangnya.
Informasinya, RPP KEN dalam proses persetujuan penandatanganan beberapa menteri terkait untuk dijadikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Peraturan lainnya yang mengamanatkan tentang PLTN, telah diterbitkannya Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN). Hanya target penyediaan energi nuklir di RUKN lebih sedikit dibandingkan RPP KEN, sebesar 8 persen atau sekitar 35 GW hingga tahun 2060.
Bob menyebutkan, “Pembangunan PLTN-nya tersebar di tujuh wilayah, di Banten, Sumatera Utara, Batam, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Halmahera Timur.”
Poin ketiga, disebutkan Bob, saat ini sudah ada beberapa perusahaan nuklir berminat membangun PLTN di Indonesia. Seperti PT Thorcon Power Indonesia, Rosatom State Atomic Energy Corporation (Rosatom) dari Rusia, China National Nuclear Corporation (CNNC), Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP), dan NuScale Power dari Amerika Serikat.
“Namun, semua perusahaan nuklir ini masih wait and see. Karena masih belum ada kejelasan dari Pemerintah Indonesia, semua menunggu NEPIO,” ungkapnya.
Empat Kontradiktif Kebijakan PLTN di Indonesia
Bob kembali melanjutkan wacana perusahaan nuklir yang berminat membangun PLTN di Indonesia. Masalahnya, Bob membeberkan, perusahaan nuklir dari Rusia, China, Korea Selatan, dan AS umumnya menawarkan desain PLTN kapasitas besar, minimal 1.000 MW. Rosatom, misalnya, desain PLTN-nya tidak mempunyai skala Small Modular Reactor (SMR). Rosatom mempunyai desain PLTN skala kecil, tipe floating di atas kapal. Hanya saja, Indonesia belum mempunyai regulasi tentang floating.
“Ini kontradiktif pertama, persoalan kapasitas. Pemerintah Indonesia menginginkan SMR. Bahkan dalam RUU Penyediaan Tenaga Listrik disebutkan kapasitas nuklirnya 250 MW. Pemerintah Indonesia juga menginginkan reaktor nuklir yang proven atau terjamin. Sementara reaktor nuklir yang sudah proven rata-rata tidak ada tipe SMR. Kecuali CNNC. Dia akan mengoperasikan reaktor nuklir ACP 100, dan sedang mendesain ACPR 100. Thorcon Power Indonesia juga mempunyai reaktor nulir tipe SMR, kapasitas 2 kali 250 MW, namun belum teruji atau belum beroperasi,” Bob menjabarkan.
Jika Pemerintah Indonesia sepakat kapasitas reaktor nuklir sebesar 250 MW, Bob mengklaim Bangka Belitung dan Kalimantan Barat dapat masuk. Saat ini seluruh Kalimantan kapasitas listriknya masih di bawah 3 GW. Bahkan untuk Pulau Kalimantan, kapasitas PLTU rata-rata masih 100 MW. Sementara kapasitas PLTU di Pulau Jawa rata-rata sudah ribuan MW.
“Jika bicara kapasitas besar, 1.000 MW, maka PLTN tidak bisa dibangun di Kalimantan. Yang bisa kapasitas 1.000 MW hanya di Pulau Jawa dan Sumatera. Karena Sumatera termasuk Bangka yang sudah terkonek ke Sumatera, kapasitasnya saat ini sudah mencapai sekitar 8 GW,” imbuhnya.
Kontradiktif kedua, masalah pembiayaan. Rata-rata pembiayaan PLTN di dunia, dibiayai oleh negara atau menggunakan APBN. Sementara kondisi ruang gerak fiskal Indonesia saat ini terbatas. Apalagi, jika yang dibangun PLTN kapasitas 1.000 MW, biayanya antara 5.000 hingga 7.000 dolar AS.
Jika diambil biaya paling murah pun, 5.000 dolar AS, Bob mengestimasi untuk PLTN kapasitas 1 GW biayanya sekitar Rp 80 triliun. Sementara perusahaan-perusahaan nuklir dibangun berdasarkan sistem Engineering Procurement Construction (EPC)– menjual teknologi.
Dari kacamata Bob, Pemerintah Indonesia bisa saja menggunakan sistem Independent Power Producer (IPP). Perusahaan nuklir hanya menjual listrik ke pemerintah. Toh, spektrum pembiayaan ada tiga metode, yaitu spektrum jual teknologi (EPC), spektrum IPP, dan spektrum terbuka, yang bisa menerima kedua metode pembiayaan tersebut.
“Tapi, di Indonesia hanya ada dua metode pembiayaan, yaitu antara EPC dan IPP. Masalahnya, pembiayaannya dari mana? Sampai sekarang belum ada solusi,” bebernya.
Metode pembiayaan ada beberapa skema, salah satunya Public Private Partnership (PPP). Skema pembiayaan ini dilakukan melalui kerja sama antara pemerintah dengan badan usaha. Kata Bob, pemerintah bisa meminta Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) untuk bekerja sama dengan badan usaha dalam investasi pembangunan PLTN.
“Nah, skema mana yang sesuai untuk pembangunan PLTN di Indonesia, ini juga belum dibahas. Satu hal yang harus ditetapkan pemerintah, pembangunan PLTN secara tegas dinyatakan tidak menggunakan APBN,” tegasnya.
Kontradiktif ketiga adalah tarif listrik. Bob melihat sampai saat ini belum ditetapkan secara jelas besaran tarif listrik dari PLTN yang dianggap layak. Dia menekankan, seharusnya PLTN posisinya sebagai baseload ketika saatnya menggantikan peran PLTU. Dengan demikian, tarif listrik PLTN bersaing dengan tarif listrik PLTU.
Menurutnya, di balik penentuan tarif listrik adalah menekan subsidi dan atau kompensasi. Saat ini, subsidi dan kompensasi listrik yang diberikan pemerintah mendekati Rp 100 triliun. Diperkirakan 10 tahun ke depan bisa mencapai Rp 200 triliun.
Karena itu, kehadiran PLTN harus bisa menekan biaya subsidi listrik. Jika PLTN yang dibangun kapasitas besar berbiaya 5.000 dolar AS per KW atau 5.000.000 dolar AS per MW, estimasi Levelized Cost Of Electricity (LCOE) sekitar $12 hingga $13 cent per kwh jauh di atas rata-rata BPP nasional yang hanya di kisaran $7 cent per Kwh. Maka Pemerintah Indonesia harus siap-siap menggelontorkan biaya subsidi/kompensasi listrik yang mengalir atau feed–in–tarif apapun namanya yang besarannya bisa Rp 8 triliun per tahun per 1GW.
Bob menyampaikan, “Untuk membebaskan subsidi, tarif listrik PLTN harus di kisaran Rp 1.000 per kWh, atau maksimum $8 cent.”
Berikutnya kontradiktif keempat, disebut Bob, soal kesiapan teknologi PLTN. Jika Pemerintah Indonesia menentukan PLTN yang dibangun harus proven, konsekuensinya biaya pembangunan hingga tarif listrik mahal, dan akan ada subsidi.
Bob menduga, di balik isu kesiapan teknologi, pertama, ada rasa ketakutan. Seolah-olah jika belum proven ibarat membeli kucing dalam karung. Seolah-olah teknologinya tidak lebih aman. Kedua, muncul persepsi bahwa teknologi PLTN yang boleh dibangun di Indonesia yang sudah proven.
“Kedua penilaian itu salah. Karena orang yang berpandangan seperti itu tidak paham keselamatan nuklir serta regulasi. Jika benar bahwa yang sudah proven lebih aman, maka peristiwa Fukushima tidak mungkin terjadi. Karena teknologi PLTN Fukushima sudah proven. Jadi, proven atau belum proven, tidak menjamin keselamatan. Yang menjamin keselamatan hasil evaluasi desain, tahapan berbagai pengujian dan sudah melalui tahapan proses perizinan,” paparnya.
Ia menyatakan, yang memiliki tanggung jawab keselamatan bukan pemerintah, PLN, Kementerian ESDM, BRIN, atau Batan. Tetapi, kewenangan ada pada Bapeten. Sepengetahuannya, Bapeten tidak pernah menyatakan teknologi A proven, teknologi B tidak proven, dalam regulasi Bapeten istilah tersebut tidak ada. Baik yang proven atau belum, keduanya harus melalui tahapan perizinan yang hampir sama.
Dirinya mengutip Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perizinan Instalasi Nuklir dan Pemanfaatan Bahan Nuklir, hanya menyebutkan reaktor komersial dan nonkomersial. Reaktor komersial adalah reaktor nuklir yang dibangun badan usaha, koperasi, dan BUMN. Sedangkan reaktor nonkomersial dibangun oleh Batan.
“Reaktor komersial adalah reaktor yang sudah dibangun negara lain minimal 2 tahun. Jadi, tidak ada kata proven. Namun, sudah beroperasi di negara lain, inilah yang akhirnya dijadikan dasar istilah teknologi proven,” tepisnya.
Tetapi PP No 2 tahun 2014 sudah tergantikan khususnya untuk Badan Usaha. Bob juga menyinggung regulasi nuklir di beleid Omnibus law (UU Cipta Kerja), yang salah satu turunan PP adalah PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, ketentuan ini menyebutkan bahwa Bapeten diamanahkan sebagai pengampu (koordinator) untuk ketentuan perizinan.
Maka, dia lantas menekankan, berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 2021 yang berwenang melakukan koordinasi perizinan adalah Bapeten, bukan Kementerian ESDM. Bahkan sudah ada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, yaitu KBLI 43294 untuk PLTN di mana dalam KBLI ini Bepeten harus berkordinasi dengan ESDM dan PLN.
Pun dalam PP Nomor 5 Tahun 2021, disambung Bob, badan usaha swasta diizinkan membangun reaktor purwarupa atau yang belum proven untuk kemudian setelah mendapatkan izin operasi dapat di komersialkan dengan menjual listrik ke PLN. Jadi menurut Bapeten untuk badan usaha, termasuk BUMN, dasar hukum perizinan PLTN adalah PP No 5. Sementara PP No 2 hanya berlaku untuk pemerintah seperti BRIN, bukan untuk badan usaha.
“Jadi, berdasarkan PP No 5, perusahaan swasta atau BUMN dapat membangun PLTN yang belum proven untuk kemudian menjual listrik ke PLN,” kata Bob.
Intinya, masih menurut Bob, apapun keputusan pemerintah terkait PLTN, membangun large scale yang proven tapi mahal atau SMR yang murah tapi belum proven, semua opsi akan ada konsekuensi.
“Maka, kita harus siap dengan konsekuensi tersebut, termasuk subsidi bagi PLTN, dan saya siap membantu pemerintah sebagai konsultan dalam mengambil keputusan tersebut,” kata Bob mengakhiri perbincangan dengan corebusiness.co.id (Syarif)